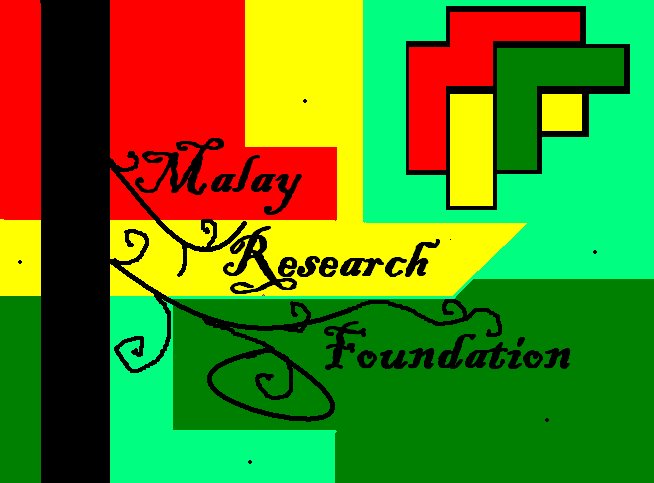Oleh Eddy Satriya
Menarik sekali menyimak pernyataan Rektor Universitas Indonesia (UI) Usman Chatib Warsa tentang minimnya kehadiran dosen utama dalam program kuliah Strata Satu (S-1) di universitas terkemuka tersebut. Dosen utama yang dimaksudkan adalah dosen berpengalaman yang memiliki tambahan gelar akademik S-2 dan S-3, termasuk para guru besar.
Sang Rektor menyatakan bahwa masalah ekonomi, yaitu kurangnya gaji yang diterima dosen dari pemerintah merupakan penyebab utama, di samping masih belum seimbangnya rasio dosen dan mahasiswa.
Kekurangan gaji akhirnya ditutupi dengan mengajar atau bahkan juga terlibat dalam pelaksanaan proyek di berbagai perguruan tinggi lain. Padatnya jadwal tambahan mengakibatkan dosen bersangkutan mengalami kesulitan dalam membagi waktunya untuk mahasiswa UI sendiri.
Walaupun minimnya kehadiran dosen utama tidak terjadi pada seluruh fakultas, pengakuan jujur oleh rektor yang baru terpilih ini tentu saja mencuatkan keprihatinan yang mendalam bagi kita semua. Keprihatinan yang patut dan wajar karena kondisi ini ternyata masih saja berlangsung di saat berbagai krisis masih bercokol di bumi Indonesia. Sementara era globalisasi dan perubahan tatanan ekonomi baru dunia dewasa ini semakin menuntut sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing tinggi.
Bagi sebagian rakyat Indonesia yang pernah beruntung mendapat kesempatan sekolah ataupun menjalani pelatihan di luar negeri, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), tentulah dapat merasakan perbedaan dosen di sana dengan dosen di Tanah Air dalam menjalankan tugasnya.
Mereka memang lebih mampu membagi waktunya untuk tugas mengajar, menghadiri konferensi, tugas administrasi, tugas penelitian serta tugas-tugas lain di negara bagian dimana universitas tersebut berada. Sudah menjadi kebiasaan dosen di AS untuk memampangkan sebuah board yang berisikan informasi tentang telepon dan e-mail dosen bersangkutan guna kemudahan komunikasi serta informasi jam kerja atau office hour di pintu kamarnya.
Jam kerja tersebut tidak saja memuat jadwal kuliah dan praktikum untuk semester berjalan, tetapi juga memuat slot waktunya yang disediakan untuk mahasiswanya. Di atas segalanya, jadwal atau janji yang sudah disepakati biasanya ditepati sang dosen dengan kehadiran kadang-kadang di atas 100 persen.
Jika sang dosen berhalangan, biasanya ia akan berusaha memberitahukan jauh-jauh hari. Tidak jarang mahasiswa menerima telepon bernada minta maaf dari seorang dosen yang karena berhalangan mendadak terpaksa harus membatalkan janji. Saya pribadi pernah mengalami hal tersebut.
Membicarakan perbedaan antara dosen di AS dengan koleganya di Indonesia pada saat-saat sekarang ini untuk sebagian orang mungkin tidak relevan, tidak populer atau bisa dianggap mengada-ada. Namun pengakuan jujur dari rektor baru UI itu dalam upaya memajukan universitasnya dan mewujudkan misi akademiknya di era otonomi kampus, tentu saja merupakan suatu moment yang sangat penting dan perlu ditindaklanjuti. Ada beberapa alasan untuk itu.
Pertama, permasalahan mangkirnya dosen utama dari tugasnya jarang ditindaklanjuti secara nyata. Kasus ini bukanlah masalah UI semata, tapi juga terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka.
Dengan menyebutkan alasan ekonomi, secara implisit Rektor UI telah mengakui terjadinya penyalahgunaan waktu oleh oknum dosen utama atau dosen senior untuk menutupi kekurangan gajinya. Jika tidak ditangani secara serius dan bertahap tentulah hal ini akan dapat menghambat program reformasi di perguruan tinggi. Kedua, dosen senior dengan jam terbang tinggi biasanya mahir menyampaikan informasi yang sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan mahasiswa yang kadang-kadang menjadi lebih penting ketimbang bahan kuliah semata.
Seorang teman dekat saya yang lulusan Planologi ITB, pernah menyatakan kekagumannya kepada salah seorang profesornya. Sedikit berlebihan, ia berkomentar bahwa dengan sekali saja menghadiri kuliah sang profesor tersebut, ia merasa sudah mendapatkan pengetahuan luas yang bisa merangkum berbagai bahan kuliah yang diperoleh selama dua sampai tiga tahun di ITB.
Pengalaman saya menjadi dosen tamu di UI dan beberapa PTS di Jakarta menunjukkan bahwa mahasiswa kita memang sebaiknya dibekali dengan berbagai perkembangan aktual yang terjadi di masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, sudah selayaknya universitas memberikan perkuliahan yang berkualitas dan tertib administrasi, mengingat mahasiswa di era reformasi ini membayar biaya pendidikan relatif lebih mahal dibandingkan zaman Orde Baru.
Terlebih lagi berbagai insentif, fasilitas dan tunjangan untuk mahasiswa seperti bea siswa, keringanan biaya kuliah (SPP), asrama yang bersubsidi, tunjangan percepatan kelulusan dan kredit mahasiswa (KMI) sudah semakin berkurang. Fasilitas tertentu malah telah dihilangkan karena alasan yang kadang-kadang tidak masuk akal.
Terakhir, proses seleksi mahasiswa baru khususnya untuk program S-1 yang konsisten dilaksanakan sejak tahun 1970-an melalui SKALU, PP I, Sipenmaru dan lain-lain, harus diakui telah mampu manjaring calon-calon mahasiswa terbaik di republik ini. Alangkah sia-sianya jika bibit yang bagus tertanam di tanah yang gersang.
Sebenarnya disamping alasan untuk mencukupi kekurangan gaji dan belum optimalnya rasio dosen-mahasiswa, tentu masih ada beberapa alasan lain yang menjadi penyebab mangkirnya oknum dosen senior dari ruang kuliah. Salah satunya adalah menjadi birokrat pada waktu yang bersamaan.
Tatkala sudah memasuki zona birokrasi di negeri yang berperingkat ”sangat meyakinkan” dalam hal korupsi, masalah ini tentu menjadi semakin serius dan memprihatinkan. Sayangnya kondisi ini terlupakan seiring hiruk pikuk berbagai persoalan bangsa terutama sejak memasuki era reformasi dan sejak dimulainya tahap inisiasi pelaksanaan otonomi daerah. Padahal mantan Presiden Abdurrahman Wahid secara gamblang sudah mengingatkan bahwa, ”Banyak Profesor dan Doktor Menjadi Maling.”
Jika dilihat kembali ke masa awal orde baru berkuasa, memang banyak dosen utama yang diminta membantu pelaksanaan tugas pemerintah. Hal ini bisa dipahami karena pada masa itu jumlah SDM dengan kemampuan akademik dan intelektual yang memadai memang masih terbatas.
Ada nama-nama besar seperti Sumitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Sumarlin, dan Emil Salim yang pernah menduduki berbagai jabatan penting terutama di bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Menko Ekuin.
Namun jika diamati lebih saksama di masa-masa akhir berkuasanya Presiden Suharto, jumlah dosen, termasuk yang belum senior, yang menduduki jabatan di birokrasi pemerintah masih relatif besar. Para dosen ini bukan saja menduduki jabatan politis menjadi pejabat negara seperti Menteri,
Gubernur, dan pimpinan di berbagai Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) tetapi juga menduduki jabatan-jabatan struktural yang seyogianya diperuntukan bagi pejabat karier.
Jumlah ini hanya mungkin dapat disaingi oleh aparat militer yang berdwifungsi dan menduduki jabatan serupa di birokrasi. Ironisnya hal ini terus berlangsung sampai sekarang, malah semakin menjadi-jadi seiring dengan banyaknya tambahan Departemen dan LPND baru. Sementara TNI, di sisi lain, sudah mulai mereposisi diri.
Tentu wajar saja kalau timbul pertanyaan. Apakah SDM di Departemen dan LPND saat ini memang tidak berkualitas dan sama kondisinya dengan 30 tahun lalu? Atau bahkan lebih buruk? Presiden Megawati pernah menyebut birokrasinya sebagai birokrasi ”keranjang sampah”.
Patut kiranya menjadi pengetahuan kita bahwa sejak 1980-an telah cukup banyak dana yang digunakan untuk membiayai pengiriman pegawai negeri sipil (PNS) melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu S-2 dan S-3, baik di dalam maupun di luar negeri.
Biaya tersebut umumnya berasal dari pinjaman luar negeri yang jika dijumlahkan dari berbagai sumber bisa mencapai ratusan juta dollar. Tidak terhitung pula PNS yang memperoleh beasiswa dari berbagai lembaga atau foundation internasional lainnya. Perlu pula diingat bahwa biasanya selama bersekolah, gaji PNS tetap dibayarkan oleh negara.
Apakah mereka memang tidak berkualitas atau tidak memperoleh kesempatan sehingga pantas mengisi birokrasi ”keranjang sampah”? Wallahualam. Yang pasti hampir 90 % dari mereka yang disekolahkan tersebut adalah putera puteri bangsa terpilih yang lulus saringan SKALU, PP I dan Sipenmaru.
Dosen yang memasuki birokrasi biasanya akan mengalami ”cultural shock”. Pengalaman yang diperoleh selama mengerjakan proyek-proyek pemerintah di berbagai lembaga penelitian dan konsultan di kampus tidak pernah cukup untuk menghadapi masalah dan tantangan birokrasi yang luar biasa kompleksnya.
Di samping substansi dan teknis, pejabat sehari-harinya juga harus memikirkan masalah manajemen, keuangan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan keproyekan. Tugas berat ini tentu saja menuntut dedikasi dan jam terbang tinggi mengingat pelaksanaan reinventing government masih jauh dari memuaskan. Sayangnya hal ini sering dipungkiri dan terkadang di anggap sepele.
Hal terberat akan dihadapi manakala sang dosen berurusan dengan keproyekan. Inilah yang menjadi pusat keprihatinan kita. Pekerjaan management proyek yang meliputi proses penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP), Satuan-2, Satuan-3, pembahasan Daftar Isian Proyek (DIP), revisi serta monitoring pelaksanaannya sangatlah kompleks.
Terkadang pekerjaan ini, khususnya pembahasan DIP di Departemen Keuangan, untuk sebagian orang bisa dikategorikan intellectually harassing. Kemuliaan intelektual yang begitu tinggi dan idealisme yang dimiliki di kampus harus berhadapan dengan permainan ”mark up”, ”kongkalingkong”, nepotisme, intrik dan berbagai bentuk praktik suap menyuap yang sering disingkat dengan KKN yang terkenal itu.
Idealisme tinggi yang biasanya masih terpelihara dan mengkristal dalam sanubari sang dosen pelan-pelan akan ikut lebur, meleleh, mencair dan menguap setelah masuk ”sarang penyamun”. Tekanan keproyekan kadang bukan hanya datang dari bawah dan samping, tetapi juga dari atas. Baik dalam suatu kantor, maupun dari kantor pemerintah lainnya. Hal yang memang kerap terjadi di masa Presiden Gus Dur dan Megawati yang sarat dengan muatan politik partai.
Seiring dengan jabatan di pemerintahan, berbagai jabatan susulan juga akan bermunculan. Yang paling sering adalah tawaran menjadi komisaris di puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta. Menjadi komisaris, biasanya sang dosen akan terbuai dengan berbagai fasilitas yang memang ”enak tenan” yang bisa melupakan mahasiswa atau rencana untuk menerbitkan buku teks kuliah. Terkadang jabatan komisaris terasa dipaksakan.
Sebagai contoh, seorang profesor ahli pertanian yang menduduki jabatan setingkat direktur atau direktur jenderal bisa saja menduduki jabatan komisaris suatu perusahaan di bidang jasa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dengan pertanian. Jam terbang? Itu bisa diatur.
Di zaman orde baru, di saat proses privatisasi dan restrukturisasi yang dimotori Bank Dunia melanda banyak BUMN vital, banyak pula direksi BUMN secara cerdik berhasil ”mendudukkan” sang dosen, yang juga pejabat yang berwenang di sektor terkait, menjadi komisaris BUMN yang dipimpinnya. Taktis memang, karena akan memuluskan urusan direksi disatu sisi, tapi biasanya meninggalkan banyak pemasalahan dengan bawahan sang komisaris di sisi lain.
Sebenarnya ada pekerjaan lain yang berpotensi menyita waktu dosen dan membuatnya mangkir dari tugas. Antara lain sebagai peneliti yang mengerjakan proyek di lembaga penelitian yang ada dilingkungan universitas maupun di luar, dan yang sekarang sedang ”naik daun” adalah menjadi presenter dan pembicara di berbagai acara talk show.
Namun dibandingkan dengan menjadi birokrat, pekerjaan jenis ini tidak terlalu berpotensi KKN dan terkadang memang diperlukan untuk kematangan diri. Namun ketatnya jadwal atau buruknya time management terkadang membuat mereka kurang konsentrasi dan terpaksa mangkir dari tugasnya.
Dengan berbagai kesibukan sang dosen di luar kampus, tidak heran banyak mahasiswa saat ini terlihat bolak balik ke kantor pemerintah untuk berkonsultasi. Bahkan tidak jarang pula mahasiswa terpaksa kuliah di kantor pemerintah tempat sang dosen menjabat. Di pihak lain, dosen utama atau profesor yang berhasil menulis buku atau menerbitkan artikel di jurnal tingkat nasional apalagi internasional selama menjabat di birokrasi, bisa dihitung jari.
Keprihatinan Rektor UI tentang minimnya kehadiran dosen utama di universitasnya tentu juga menjadi keprihatinan rektor-rektor PTN dan PTS lainnya di seluruh Indonesia serta keprihatinan kita semua yang sangat ingin pendidikan tinggi di Indonesia maju secara lebih berarti.
Tulisan ini bertujuan hanyalah untuk menggugah rasa keprihatinan itu untuk kemudian ditindaklanjutinya secara bijak. Tidak lebih tidak kurang.
Mengharapkan regulasi maupun aturan tertulis dari PTN dan berbagai instansi terkait dalam situasi sekarang ini, tentulah akan memakan waktu dan menunda proses perbaikan bangsa. Karenanya menjadi penting sekali mewujudkan kesadaran di dalam hati kita untuk bertindak profesional di dalam tugas, memulai budaya malu KKN dalam arti sebenarnya serta tepo seliro terhadap 40-an juta penganggur terdidik dan tidak terdidik yang juga harus menghidupi keluarganya. Namun, kita tentulah tidak melupakan bahwa masih banyak dosen utama yang sangat menjunjung tinggi profesinya. Salut untuk mereka.
Sebagai penutup, tidak ada salahnya kita simak pertanyaan dari salah seorang profesor ITB yang saya jumpai dalam satu seminar di Bandung beberapa tahun lalu. Beliau menanyakan tentang perbedaan profesor (dosen), peneliti dan birokrat.
Seperti biasa, profesor yang sudah cukup sepuh tidak akan sabar untuk menasihati kita dan tidak perlu menunggu jawaban. Pertanyaan itupun dijawabnya sendiri. Pelan meluncur dari bibirnya, ”Dalam tugasnya, profesor tidak boleh salah dan tidak boleh bohong. Peneliti boleh salah, tetapi tetap tidak boleh bohong. Sedangkan birokrat, boleh salah, boleh bohong!”.
Astaga! Nah, bagaimana jika guru besar menjadi politisi?
Penulis adalah dosen tamu Program Magister Teknologi Informasi di Fasilkom-UI,
tinggal di Sawangan, Depok.
Selasa, 02 September 2008
Dosen, Peneliti, dan Birokrat
Diposting oleh Ristu hasriandi Khoo di 14.34 0 komentar
Label: About Research
Langganan:
Komentar (Atom)